HARIANRIAU.CO - Pada umumnya umat Muslim berzikir kepada Allah dengan mengeraskan suara karena sedang mendapat cobaan atau ujian. Namun sebenarnya berzikir dengan suara keras juga baik dipanjatkan untuk mensyusukuri nikmat yang diterima.
Imam Abu Na’im al-Ashbahânî (330-430 H), mencatat suatu riwayat yang menceritakan Imam Ibnu al-Munkadir berzikir dengan suara keras. Kisah itu tertulis dalam kitab Hilyah al-Auliyâ wa Thabaqat al-Ashfiyâ’:
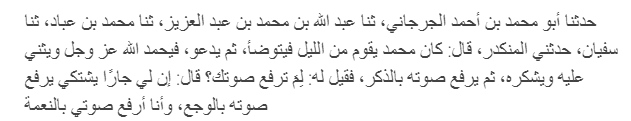
Abu Muhammad bin Ahmad al-Jurjani bercerita, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz bercerita, Muhammad bin ‘Ibad bercerita, Sufyan bercerita, al-Munkadir bercerita kepadaku, ia berkata:
“(Suatu ketika) Muhammad (bin al-Munkadir) bangun pada malam hari, ia berwudhu lalu berdoa, memuji Allah Azza wa Jalla, memuliakan-Nya dan bersyukur kepada-Nya, kemudian mengeraskan suaranya dengan dzikir.”
Ia ditanya: “Kenapa kau mengeraskan suaramu?”
Ia menjawab: “Sesungguhnya aku memiliki tetangga yang (suka) mengeluh, ia mengeraskan suara (keluhan)nya sebab penderitaan, sedangkan aku mengeraskan suaraku sebab nikmat.” (Imam Abu Na’im al-Ashbahânî, Hilyah al-Auliyâ wa Thabaqat al-Ashfiyâ’, Kairo: Dar al-Hadits, 2009, juz 2, halaman 427)
Sebelum menguraikan lebih jauh, perlu diingat terlebih dahulu bahwa semua orang pasti pernah mengalami musibah, penderitaan, dan kekecewaan, siapapun dia, baik anak raja, maupun anak orang bisa.
Tak terkecuali Sayyidina Muhammad bin al-Munkadir (w. 130 H), seorang tabi’in yang mendengar hadits secara langsung dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Anas bin Malik, dan lain sebagainya. Ia juga pernah mengalami musibah dan ujian.
Perbedaannya adalah, Sayyidina Muhammad bin al-Munkadir memandangnya sebagai nikmat, sedangkan kebanyakan insan memandangnya sebagai musibah. Itulah hikmah terpenting yang harus diambil dari kisah di atas. Bagi orang-orang tertentu, mereka akan bersyukur ketika diberi cobaan.
Salah seorang sufi mengatakan, “Wa in ashâbanâ syarrun syakarnâ” (dan jika keburukan menimpa kami, maka kami akan mensyukurinya). (Syekh Mutawalli Sya’rawi, Tafsîr al-Sya’râwî, juz 16, halaman 9.729)
Melihat sikap Sayyidina Muhammad bin al-Munkadir dan ulama-ulama lainnya, Muslim seperti digiring untuk memahami musibah sebagai madrasah, semacam pendidikan praktis dalam mengamalkan agama yang mendewasakan jiwa.
Tanpa musibah dan cobaan, mungkin pemahaman sebagian besar umat Islam terhadap kebaikan hanya sekedar teori. Kita tidak akan mengerti pentingnya berbagi tanpa pernah dalam kekurangan. Umat Muslim tidak akan memahami manfaat bersabar tanpa pernah dihadapkan dengan cobaan, dan begitu seterusnya.
Di sisi lain, kisah di atas mengajarkan bahwa berzikir dengan suara keras sudah dilakukan sedari dulu oleh kalangan tabi’in, sebagai perwujudan syukur atas nikmat yang Allah berikan. Dalam riwayat lain, Sayyidina Muhammad bin al-Munkadir mengatakan:
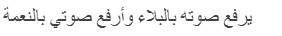
“Ia (tetanggaku) mengeraskan suaranya sebab (mengeluhkan) musibah, sedangkan aku mengeraskan suaraku sebab (mensyukuri) nikmat.” (Imam Abu Na’im al-Ashbahânî, Hilyah al-Auliyâ wa Thabaqat al-Ashfiyâ’, 2009, juz 2, halaman 427)
Penjelasan sederhananya adalah, daripada membuang-buang suara untuk mengeluhkan musibah (balâ), lebih baik menggunakannya untuk mensyukuri nikmat. Atau, jika musibah saja dikeluhkan dengan suara keras, kenapa nikmat tidak dizikirkan dengan suara keras.
Jadi, berzikir dengan suara keras, jika niatnya baik, tidak lain adalah bentuk syukur kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh sayyidul qurrâ’ (tuannya para ahli qira’ah), julukan yang diberikan Imam Malik bin Anas untuk Muhammad bin al-Munkadir (Imam Abu Na’im al-Ashbahânî, Hilyah al-Auliyâ wa Thabaqat al-Ashfiyâ’, 2009, juz 2, h. 427).
Mensyukuri nikmat Allah dengan berzikir merupakan langkah awal, karena Sayyidina Muhammad bin al-Munkadir tidak berhenti sampai di sini. Ia gemar mensyukuri nikmat Allah dengan memberi manfaat untuk sekitarnya. Imam Abu Ma’syar mengatakan,
“kâna sayyidân yuth’imuth tha’âm” (ia seorang tuan yang gemar memberi makan) (Imam Abu Na’im al-Ashbahânî, Hilyah al-Auliyâ wa Thabaqat al-Ashfiyâ’, 2009, juz 2, halaman 429).
Demikian ditulis santri jebolan Pondok Pesantren Darussa’adah, Bulus, Kritig, Petanahan, Kebumen, Muhammad Afiq Zahara sebagaimana dilansir dari laman resmi Nahdatul Ulama (NU Online) pada Kamis (22/1/2020).
sumber:










